Jakarta “Film. Mungkin anugerah seni terbesar yang pernah dimiliki manusia.”
Ada buku kumpulan cerpen asyik tentang dunia perfilman yang ditulis almarhum Misbach Yusa Biran. Judul bukunya …Oh, Film (terbit dua kali, 1973 [Pustaka Jaya] dan 2008 [KPG]) yang aslinya ia tulis pada penghujung tahun 1950-an. Salah satu cerpen di buku itu berkisah tentang pertemanan Jupri, seorang pria yang ingin dianggap sebagai wartawan, dengan Brotowali, bintang film yang sombongnya minta ampun tapi sebetulnya tak pandai berakting. Dengan membawa kepentingan masing-masing, mereka cepat akrab.
Suatu kali, film yang dibintangi Brotowali main di bioskop. Jupri mengajak kawan-kawannya yang wartawan betulan nonton dan minta mereka menuliskan resensi filmnya. Teman-teman Jupri memang menulis resensi film itu. Tapi, yang mereka tulis umumnya caci maki. Begini, Misbach menggambarkannya:
“(Di) Penerbitan berikut tertera resensi film tersebut, juga gambar Brotowali dipampangkan. Gambar Brotowali terang sekali, fotonya bagus, dan di bawahnya tercantum kecaman-kecaman yang terang pula tentang permainannya yang dianggap amat merusak seluruh film. Diibaratkan setetes darah babi dalam air: rusak semua oleh perannya yang cuma sedikit. Diusulkan agar adegan di mana Broto ada dibuang saja.”

Yang terjadi kemudian, Brotowali mengeluh pada Jupri. Ia bilang, ayahnya tak bisa menerima anaknya dikritik pedas macam begitu. “Ia tetap tidak mau mengerti kalau anaknya dimaki-maki orang. Saya kuatir betul karena… ya, ayah saya orang galak. Baru umur sepuluh tahun saya bisa ketemu dia, selama itu ia dalam penjara karena membunuh orang yang menghina kakaknya…”
Cerita di atas bisa jadi bentuk ekstrem betapa sebuah resensi film yang pedas tak bisa diterima oleh sebuah pihak. Cerita begini bentuknya macam-macam dan rupanya sudah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun lampau.
Pangkal soalnya adalah pembuat film kerap memanfaatkan kritikus sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah karya. Hanya saja, penilaian kritikus itu baru disambut gembira bila hasilnya berupa pujian. Sebab hal itu bisa dijadikan alat pemasaran (bisa ditempelkan di poster film atau sampul DVD). Lain halnya ketika kritikus menilai jelek terhadap karyanya. Pembuat film bisa mencak-mencak, “Memangnya bikin film itu gampang! Enak saja bilang film saya jelek, coba bikin sendiri kalau bisa!”
Pembuat film yang marah-marah ketika filmnya dikritik pedas sejatinya tak butuh kritik film. Yang ia butuhkan adalah publikasi alias pemberitaan atau ulasan serba baik dan bagus menyangkut filmnya. Lain tidak.
Kisah Film Buruk Rob Schneider
Persoalan ini, menurut Goenawan Mohamad dalam sebuah esainya di majalah Tempo pada tahun 1970-an, bermuara pada kenyataan bahwa film adalah barang dagangan, bukan hanya karya seni. Sebagai barang dagangan, lanjut Goenawan, film tak butuh kritik, tak butuh pembahasan dari segi artistik, sinematografi, logika, kejujuran penciptaan dan kecerewetan macam itu. Sebagai barang dagangan ukuran yang digunakan adalah “laris” dan “tidak laris”. Sedang kritik film menggunakan ukuran “bermutu” dan “tidak bermutu”.
Perbedaan tolak ukur ini saja sebenarnya sudah menjelaskan hubungan antara pembuat film (terutama yang memandang film sebagai barang dagangan) dengan kritikus film: hanya baik bila kritikus memberi nilai bagus. Karena ya itu tadi, penilaian yang bagus tersebut bisa dijadikan alat pemasaran tambahan pada film.
Menjadikan kritikus sebagai alat pemasaran berarti pula menempatkan kritikus pada posisi dalam bagian mata rantai produksi film. Padahal pada hakekatnya tidak demikian. Posisi kritikus berada di luar proses produksi dan karenanya ia independen dalam menilai sebuah film. Hanya saja, masih banyak sineas yang tak menganggap begitu. Dengan dalih sebagai bagian dari memajukan dunia perfilman, pembuat film mengharapkan kontribusi kritikus yang bila disederhanakan maksudnya: kritik yang memuji.
Ada banyak cerita soal hubungan kurang baik antara sineas dengan kritikus. Goenawan Mohamad pernah menerima keluh kesah kenalannya yang pembuat film usai dikritik pedas. “Mungkin maksudnya ingin mematikan karier saya,” kata Goenawan mengutip kawannya itu.
Di Hollywood sana contohnya juga banyak. Suatu ketika, seperti diulas kritikus Roger Ebert, kritikus film Los Angeles Times Patrick Goldstein menulis film-film terbaik nominator Oscar tahun 2005 yang menurutnya “tak dihiraukan, tak disukai dan ditolak pembuatannya oleh studio film lantaran … mereka lebih suka menghabiskan uang untuk membuat film-film sekuel, termasuk sekuel Deuce Bigalow: Male Gigolo, sebuah film yang sayangnya tak diacuhkan saat penganugerahan Oscar karena tak seorang pun terpikir untuk membuat kategori Best Running Penis Joke Delivered by a Third Rate Comic—lelucon kemaluan laki-laki berlari yang dibawakan komedian kelas tiga.”

Komedian yang dimaksud adalah bintang utamanya, Rob Schneider. Sang pelawak ini lantas menganggap cercaan padanya sudah kelewatan dan karenanya harus ditanggapi serius. Ia membuat iklan satu halaman di koran Daily Variety dan Hollywood Reporter berupa surat terbuka yang isinya antara lain: “Well, Mr. Goldstein, saya memutuskan melakukan riset dan menemukan kalau Anda tak pernah memenangkan penghargaan apa pun. Saya cari di Internet dan tak menemukan data yang menyebutkan Anda pernah memenangkan apa pun. Tak pernah sekalipun. Tidak ada penghargaan jurnalistik atau semacamnya (yang pernah Anda menangkan)… Mungkin Anda tak pernah menang Pulitzer Prize (Oscar-nya buat wartawan) lantaran mereka, para juri di sana, belum menemukan kategori untuk Best Third-Rate, Unfunny Pompous Reporter Who’s Never Been Acknowledged by His Peers—Terbaik untuk orang-orang kelas tiga, reporter yang karyanya tidak lucu yang tak pernah dikenal oleh kawan sesama profesi.”
Ebert lantas membela Goldstein saat meresensi film Deuce Bigalow: European Gigolo di korannya Chicago Sun-Times. Ia menulis: “Saya cari di Internet dan menemukan Patrick Goldstein pernah memenangkan National Headliner Award, Los Angeles Press Club Award, RockCritics.com Award, dan penghargaan seumur hidup dari Publicists’ Guild Award.” Sedangkan Schneider, lanjut Ebert, “dinominasikan untuk Razzie Award (penghargaan untuk film-film buruk) tahun 2000 untuk Aktor Pembantu Terburuk, namun kalah oleh Jar Jar Binks, karakter virtual dalam film Star Wars Episode I: The Phantom Manace. Schneider benar soal Patrick Goldstein tak pernah menang Pulitzer Prize. Namun, sebagai orang yang pernah memenangkan Pulitzer, dan dengan begitu berarti saya masuk kualifikasi yang ditetapkan Schneider. Saya berhak bilang, dalam kapasitas sebagai pemenang Pulitzer, Mr. Schneider, film Anda buruk.”
Hubungan yang buruk itu tak hanya berlangsung lewat saling cerca di koran. Melainkan juga sudah pada tahap pencekalan terhadap sejumlah kritikus. Pembuat film menganggap kritikus pedas sebagai lawan, sedang yang menulis serba baik dianggap kawan. Sebagai contoh saja, kritikus film mendiang Pauline Kael, dari The New Yorker, mengatakan, dirinya membayar mahal untuk bersikap independen. “Sangat memalukan saat rekan wartawan lain diundang ke pemutaran film sedang dirimu tidak,” katanya pada Glenn Lovell yang menulis laporan soal campur tangan pembuat film pada kritikus untuk jurnal Columbia Journalism Review edisi Januari/Februari 1993.
Dalam laporannya, Lovell menyebut pencekalan terhadap kritkus itu berlangsung dari sekadar pelarangan memasuki pemutaran film milik studio film yang filmnya dihina sang kritikus, hingga ancaman membatalkan iklan pada media tempat sang kritikus bekerja.
Fungsi Kritikus Film
Lantas, pertanyaannya bagaimana seharusnya kritikus memposisikan diri? Sebagai teman atau lawan dari pembuat film? Jawabnya harus dikembalikan pada kenyataan kalau kritikus film bukanlah bagian dari mata rantai produksi film. Kritikus bukanlah publisis film atau staf humas dari rumah produksi yang membuat film. Ia tak digaji oleh rumah produksi, melainkan oleh media tempatnya bekerja atau sama sekali tak punya media alias menulis sekadar melepas unek-unek usai menonton film.
Lantaran tak menggaji sang kritikus, pembuat film tak berhak mencampuri isi tulisan kritikus film maupun mencekal sang kritikus bila filmnya dibilang jelek. Kritikus yang baik harus bertanggung jawab atas amanat yang diembannya dengan tetap bersikap independen. Meskipun bila pada kenyataannya kemudian, film yang dibilang buruk olehnya ternyata laris manis ditonton orang. Sebab, kita mafhum yang laris bukan berarti pula yang bermutu. Dan bila terjadi kebalikannya, film yang dinilai buruk oleh kritikus ternyata tak laku pula di pasaran, hal itu sejatinya kebetulan belaka. Kebetulan saja selera sang kritikus cocok dengan selera orang kebanyakan.
Kritikus film harus mengedepankan kepentingan film sebagai karya seni. Bukan pada pembuat film atau produser yang sudah berinvestasi besar-besaran membuat film. Meski berlebihan, pendapat Pauline Kael yang dikutip JB Kristanto ada benarnya: “Dalam kesenian satu-satunya sumber informasi yang bebas hanyalah kritik. Lainnya itu iklan.”

Kael yang dianggap salah satu kritikus film terbaik Amerika menganggap kritikus punya tugas suci. Kritikus berfungsi membantu orang melihat apa yang ada dalam sebuah karya, apa yang mestinya tidak ada dalam karya itu, dan apa yang mestinya hadir dalam karya itu.
Kritikus yang baik, lanjut Kael, membantu orang memahami sebuah karya lebih dari saat orang itu melihatnya sendiri; kritikus yang hebat yakni jika ia, dengan pemahaman dan perasaannya atas sebuah karya, juga dengan hasratnya, bisa menarik orang untuk lebih menelusuri sebuah karya yang menunggu untuk disingkap. Ia bukanlah kritikus buruk bila penilaiannya ternyata keliru. Ia jadi kritikus buruk ketika kritikannya tak membangkitkan rasa ingin tahu, mengundang ketertarikan maupun memberi pemahaman pada pembacanya. Kael lantas berkesimpulan, seni dari kritisisme terletak pada penularan pengetahuan dan menggiring rasa antusias berkesenian pada orang lain.
Dari sini kelihatan, fungsi kritikus sebagai jembatan antara masyarakat dengan pembuat film. Ia membantu masyarakat mengapresiasi sebuah film. Dalam ungkapan Marselli Sumarno (1983), kritikus film berguna untuk “menangkap dan menyampaikan kepada pembaca tingkat intelektual dan emosional sebuah film, memberi deskripsi kepada penonton film apa yang dibuat. Meski filmnya jelek, kritikus bisa menyebutkan pengalaman apa yang dapat dinikmati.”
Lantas, Bagaimana Baiknya?
Pada posisi sebagai jembatan pula posisi perkawanan kritikus dan pembuat film harus diletakkan. Kritikus membantu sineas menyampaikan gagasannya pada penonton lewat penafsiran-penafsirannya. Kepada pembuat film, kritikus punya kewajiban untuk memberi evaluasi atas hasil kerja sang sineas.
Kritikus memberi jawaban pada pertanyaan sang pembuat film: Apakah gagasan dalam film saya sampai pada penonton dengan baik? Apakah film saya memberi manfaat pada perkembangan jiwa dan alam pikiran khalayak banyak? Lantas, apakah film saya memberi kontribusi pada kemajuan film sebagai karya seni?
Kritik film yang mengedepankan film sebagai karya seni juga akan bermanfaat bagi sang kritikus. Sebab, maju mundurnya kritik tergantung sepenuhnya pada maju mundurnya objek kritik tersebut. Tidak ada kritik film yang bagus tanpa lahirnya film yang bagus. Kritikus film amat berkepentingan pada kemajuan seni film. Lewat film-film baguslah sang kritikus bisa mengasah kemampuannya mengkritik.
Pada titik ini, film dan kritik film saling melengkapi. Kritik film yang baik sama bermutunya dengan film yang baik pula. Bahkan, diharapkan, membaca kritik film sama asyiknya dengan menonton film. Pelajaran hidup yang diperoleh dari menonton film, makin lengkap bila ditambah membaca kritik film.
Oleh karena itu, hendaknya kritikus film dan pembuat film berkawan. Perkawanan yang baik antara kritikus dan pembuat film mensyaratkan kejujuran dan kemandirian. Kawan yang baik tak selalu memuji setinggi langit, melainkan berkata apa adanya. Jangan sampai, lantaran punya hubungan baik dengan produser atau sutradara film yang tengah ia ulas, sang kritikus mengendurkan standarnya. Film yang diulas, ia tulis serba baik demi menjaga hubungan baik perkawanan.
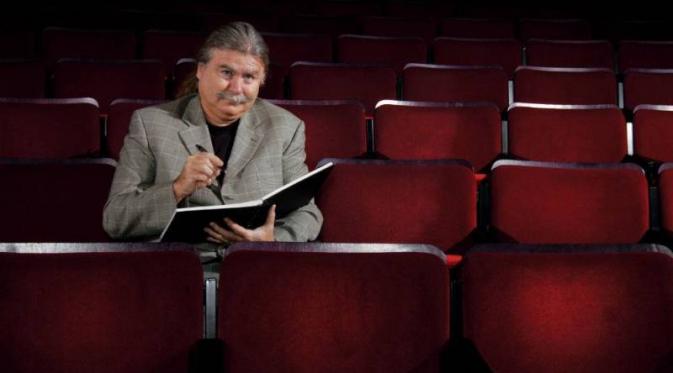
Jika demikian adanya sang kritikus tidak lagi independen. Penilaiannya tidak valid lantaran bukan berasal dari fakta-fakta objektif. Padahal, seharusnya kritik film disusun berdasarkan fakta-fakta objektif yang ditemukan saat menonton. Misalnya, bila akting si A pada kenyataannya buruk, ya jangan ditulis yang sebaliknya. Hal ini ibarat menulis berita yang tak sesuai fakta. Namanya berita bohong. Berbohong dalam urusan berita adalah dosa besar yang tak diampuni. Begitupun semestinya dalam kritik film. Tulisan kritik film yang lahir bukan dari independensi penulisnya bisa dibilang cacat hukum karena telah menodai kemurniannya sendiri.
Di sini harus timbul kesadaran dari kritikus bahwa ia mengabdi pada kepentingan kemajuan sinema sebagai karya seni. Penilaiannya yang kritis bukanlah ditujukan untuk merendahkan martabat sineas di depan umum. Melainkan harus diletakkan sebagai sebuah kajian yang bermanfaat bagi kalangan perfilman.
Pada gilirannya pihak yang paling diuntungkan atas kehadiran film bagus dan kritik film bermutu adalah masyarakat. Mereka jadi terdidik dengan kehadiran film-film yang mencerdaskan.
Oh iya, cerita pendek dari Misbach Yusa Biran di awal tulisan ini masih ada kelanjutannya.
Karena takut akan ancaman Brotowali yang mengatakan ayahnya yang galak bakal main pukul wartawan yang menjelekkan akting putranya, wartawan penulis resensi kemudian membuat pengumuman di penerbitan berikut: “Maaf, harap supaya halaman 22-23 dianggap tidak ada.” Halaman tersebut adalah halaman tempat resensi film yang dibintangi Brotowali.*** (Ade/Feb)






:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/928717/original/030015100_1436871483-Roger-Ebert4.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/928720/original/032261300_1436871706-filmcrtc_MG_0018_1800.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/928723/original/019281300_1436872047-filmjay-forry-the-blind-film-critic.jpg)



+ There are no comments
Add yours